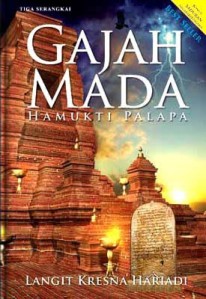
Judul : Gajah Mada #3: Hamukti Palapa (Soft Cover)
Penulis : Langit Kresna Hariadi
Penerbit : Tiga Serangkai
Tahun terbit : 2006
No. ISBN : 9793303166
Jumlah Halaman : 694
Jenis Cover : Soft Cover
Dimensi(L x P) : 140x210mm
SINOPSIS BUKU
“Untuk Mewujudkan keinginanku atas Majapahit yang besar.” ucap Gajah
Mada dengan suara amat lantang. “Untuk mewujudkan mimpi kita semua, aku
bersumpah akan menjauhi hamukti wiwaha sebelum cita-citaku dan cita-cita
kita bersama itu terwujud. Aku tidak akan bersenang-senang dahulu. Aku
akan tetap berprihatin dalam puasa tanpa ujung semata-mata demi
kebesaran Majapahit. Aku bersumpah untuk tidak beristirahat. Lamun huwus
kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring
Seram, Tanjugpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda,
Palembang, Tumasek, samana ingsun amukti palapa.” Senyap pendapa Bale
Manguntur mendengar sumpah yang disaksikan matahari yang panas menggila.
Semua orang masih terpesona pada jejak sumpah mengerikan yang diucapkan
Gajah Mada. Sumpah itu memang layak disebut mengerikan. Entah dengan
cara bagaimana Gajah Mada bisa menanggungnya. Sumpah itu terlampau
mengerikan bagi sahabat Gajah Mada karena betapa keras kerja yang harus
dilakukan untuk mewujudkannya. *** “Novel sejarah ini disajikan dengan
sangat menarik, tidak hanya terpaku pada biografi Gajah Mada tetapi
secara komprehensif juga menggambarkan situasi yang berkembang pada
zaman Majapahit.” – A. Adaby Darban. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah UGM
Resensi:
Keta, Sadeng, dan Sumpah “Hamukti Lara Lapa”
oleh: Bahtiar HS
Kemarau panjang. Gunung Kampud meletus. Kekeringan melanda setiap jengkal tanah Majapahit.
Pada situasi seperti itulah, ruang perbendaharaan pusaka Majapahit dimasuki orang. Payung Udan Riwis dan Cihna Nagara Gringsing Lobheng Lewih Laka
raib dari ruang perbendaharaan istana pada pencurian pertama! Bahkan
pada pencurian yang kedua dengan orang yang agaknya berbeda – yang
ternyata pencuri kedua ini merasa terkecoh karena Kiai Udan Riwis dan
Cihna Nagara sudah tak berada di tempatnya — Ratu Gayatri sempat
diculik dari ruang peristirahatannya! Istana Majapahit pun geger.
Mengapa justru kedua pusaka itu yang dicuri orang – sebuah payung dan
sebuah bendera — dan bukan pusaka lain yang lebih tak ternilai
harganya? Untuk apa? Dan bagaimana mungkin Ratu Gayatri selamat tanpa
kurang suatu apa dalam penculikan itu?
Telik sandi Bhayangkara pun disebar Gajah Mada. Tak kurang,
Gajah Enggon, pentolan pasukan khusus itu pun harus turun tangan
sendiri. Sesuai petunjuk Ratu Gayatri, salah seorang yang pernah
membatik bendera Cihna Nagara (lambang negara) itu, Gajah Enggon harus
memulainya dari Ujung Galuh. Di sana, kehidupannya bahkan akan dimulai
dari awal. Dia hanya tak boleh menoleh ke belakang dan diminta
mengikuti ke mana terjadi mendung dan hujan akan turun. Sebuah petunjuk
yang tentu saja penuh teka-teki.
Bersama dengan Pradabasu, seorang mantan Bhayangkara yang masih
banyak membantu Majapahit meski sudah menjadi orang luar, Gajah Enggon
melakukan perjalanan ke Ujung Galuh. Dan ternyata, di sanalah
“kehidupannya akan dimulai dari awal” memang terjadi.
Gajah Enggon bertemu dengan Kiai Agal yang misterius, yang ternyata
mengenal dirinya, dan tanpa disangkanya, sudah memiliki rencana yang
tak pernah disangkanya: orang misterius itu hendak menikahkan dirinya
dengan Rahyi Suhenok, cucunya sendiri! Dan disanalah keduanya baru
tahu, bahwa Kiai Agal tidak lain adalah Kiai Pawagal, orang dekat Raden
Wijaya. Keduanya juga bertemu dengan Medang Dangdi, teman seperjuangan
Kiai Pawagal yang bersama dengan Raden Wijaya membangun Majapahit.
Namun, tidak seperti Nambi dan teman-temannya yang lain, keduanya
memilih berada di luar pemerintahan.
Berkat informasi dari Medang Dangdilah, di Ujung Galuh itu Pradabasu
berbagi tugas dengan Gajah Enggon. Gajah Enggon tetap memburu kedua
pusaka yang hilang sebagaimana amanat Ratu Gayatri, sedangkan Pradabasu
harus segera bergerak ke Keta dan Sadeng: dua buah wilayah yang
disinyalir sedang memberontak terhadap Majapahit. Dan dari sinilah,
teka-teki mengapa kedua pusaka Majapahit itu hilang mulai terkuak.
Semuanya ada kaitannya dengan upaya Keta dan Sadeng mencari legitimasi
kekuasaan melalui penggunaan kedua pusaka itu sebagai simbol. Dan itu
harus dicegah.
Berkat upaya Pradabasu dan telik sandi Bhayangkara lainnya, pemberontakan kedua tempat itu mulai konangan. Bagaimana Patih Mogasidi dari Keta dan Patih Raganata dari Sadeng harus menelan pil pahit ketika diusir dari pasewakan Majapahit karena gerakan rahasia mereka untuk menyusun kekuatan menentang Majapahit berhasil diblejeti Gajahmada. Pasukan segelar-sepapan
pun ditugaskan ngluruk ke kedua wilayah itu. Tak kurang upaya itu
dibantu oleh armada laut Adityawarman dari Darmasraya yang sedang
berkunjung ke Majapahit. Semua berkat informasi dari Pradabasu.
Di perjalanan lain, Gajah Enggon bersama istrinya, Rahyi Suhenok,
mengejar orang yang mencuri kedua pusaka itu. Dan ternyata mereka tidak
sendiri. Ada pihak lain yang juga menginginkan kedua pusaka itu. Pihak
lain itu tak lain adalah mereka yang gagal mencuri kedua pusaka di
Majapahit. Dan pihak itu memang terbukti ada hubungannya dengan Keta
dan Sadeng.
Begitulah cerita itu bergulir. Keta dan Sadeng akhirnya berhasil
ditaklukkan. Dan kedua pusaka akhirnya kembali ke Majapahit. Dengan
sendirinya! Bagaimana bisa? Dan bagaimana bisa Ratu Gayatri sendirilah
yang menyambut Sang Pencuri kedua pusaka itu di alun-alun Majapahit
ketika hujan deras mengguyur dan membasahi bumi yang telah kerontang
begitu lama?
Jawabnya bisa ditemukan pada bagian akhir novel setebal lebih dari 600 halaman ini.
Dan pada kesempatan inilah, Patih Arya Tadah mengundurkan diri dan
digantikan dengan Gajahmada sebagai Patih Mangkubumi. Pengangkatan
dirinya tentu membuat banyak pejabat yang lebih senior kecewa, apalagi
ia menyampaikan sumpah palapanya yang terkenal itu. Sumpah yang tentu
saja di telinga mereka seperti sebuah lelucon belaka.
“Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa,
sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah nusantara ingsun amukti palapa,
lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring
Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun
amukti palapa.”
***
Inilah novel paling tebal dari keempat buku Gajahmada yang telah
diterbitkan hingga resensi ini dibuat. Lebih dari 600 halaman! Jika
sehari bisa menulis 10 halaman, novel ketiga ini ditulis Langit Kresna
Hariadi barangkali hanya dalam kurun waktu 60-an hari; alias dua
bulanan saja!
Namun, sebagaimana serial sebelumnya, novel setebal itu bisa
dikunyah selezat kedua seri sebelumnya. Bagaimanapun, Pak Langit tetap
membumbui kisah Gajahmada kali ini dengan misteri; yakni tentang
pencurian pusaka yang sebetulnya tak seberapa penting dan kaitannya
dengan pergerakan pasukan secara sembunyi-sembunyi di Keta dan Sadeng.
Dengan sisi misterius inilah pembaca dipaksa dibuat tetap erat memegang
novel ini hingga sampai pada kata terakhir.
Mungkin belajar dari kedua seri sebelumnya, pada sekuel ketiga ini
tak banyak lagi dijumpai kalimat-kalimat perulangan yang cukup
mengganggu itu. Meski demikian, tebalnya yang lumayan cukup membuat
keinginan untuk membacanya menjadi sedikit menurun. Tetapi kiranya bisa
dipahami mengapa setebal itu, karena setidaknya ada 3 pertanyaan besar
yang harus dijawab. Pertama, adanya pergerakan pasukan
berkekuatan sepuluh kapal dari Darmasraya yang dipimpin Adityawarman
yang telah tiba di Ujung Galuh. Bagaimanapun, putra Darmasraya ini
termasuk laki-laki yang masih ada hubungan darah dengan raja Majapahit
dan berhak atas dampar kencana itu. Apalagi sejak Prabu Jayanegara wafat dan kedua saudaranya, Sri Gitarja dan Dyah Wiyat, adalah perempuan semua. Kedua, hilangnya kedua pusaka – yang tak seberapa. Untuk apa keduanya dicuri. Dan ketiga, adanya gerakan di Keta dan Sadeng yang hendak melakukan makar terhadap Majapahit.
Dan inilah kelihaian Pak Langit mempertemukan ketiga isu tersebut
dalam sebuah cerita yang terjalin apik. Di samping adanya isu tambahan
akan mundurnya Arya Tadah dari kursi kepatihan. Yang memang agak
mengherankan adalah bahwa isu yang – menurut saya – tambahan atau
sampingan inilah yang justru dipilih Pak Langit menjadi judul novel
ini. Gajahmada Hamukti Palapa; yakni peristiwa sumpah amukti palapa Gajahmada yang terkenal itu. Judul yang lebih tepat, barangkali, malah Pemberontakan Keta dan Sadeng, karena isu inilah yang justru mengambil porsi terbanyak dari cerita ini.
Terus-terang saya tak pernah mendengar kisah raibnya pusaka
Majapahit itu dalam sejarah. Adalah sungguh merupakan kejutan jika
ternyata hal itu pernah terjadi dan juga kejutan pula jika tak pernah
terjadi kecuali hanya khayalan penulis saja. Karena bagaimanapun
mengaitkan isu itu dengan Pemberontakan Keta dan Sadeng, yang memang
ada tertulis di dalam sejarah, adalah sebuah ide yang jitu.
Saya pun tak pernah mendengar Adityawarman membantu Gajahmada
menyerang Sadeng dengan pasukan armada lautnya. Apalagi Sadeng terletak
di sisi selatan Jawa Timur bagian timur (selatan Jember), yang tentu
saja untuk mencapainya harus mengarungi Selat Bali dan menuju Samudera
Hindia yang terkenal ganas ombaknya. Saya masih memiliki kesan bahwa
kedatangan Adityawarman dan kerjasamanya menyerang Sadeng adalah
skenario penulisnya saja. Mudah-mudahan saya salah.
Yang juga tak kalah mengambil banyak halaman adalah penceritaan set back
bagaimana pertemuan nostalgia antara Gayatri dan Kiai Wirota Wiragati
di masa lampau ketika terjadi pemberontakan Jayakatwang, Adipati
Gelang-gelang, terhadap Raja Kertanegara. Cerita romantis yang juga
“baru” saya dengar. Jika ini tak pernah terjadi, maka saya sedikit yakin
Sang Penulisnya adalah orang yang cukup romantis. Mungkin suatu saat
saya harus bertanya pada istrinya untuk lebih yakin lagi tentang hal
ini.
Disamping hal-hal di atas, ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah membaca novel tebal ini. Pertama,
kelihatannya peran Gajah Enggon tak seberapa di dalam cerita ini. Ia
hanya “mengejar” maling Kiai Udan Riwis dan tak berhasil menangkapnya.
Karena ternyata, Branjang Ratus, Sang Maling, adalah suruhan Ratu
Gayatri sendiri. Kedua pusaka itu akhirnya kembali ke Majapahit,
dikembalikan oleh pencurinya sendiri. Lalu, untuk apa Gayatri menyuruh
Gajah Enggon menelusuri raibnya kedua pusaka itu? Untuk sekedar
menikahkan pimpinan Bhayangkara itu dengan cucu Kiai Pawagal?
Kedua, betapa mudahnya Keta dan Sadeng ditaklukkan. Seingat
saya di dalam sejarah, keduanya itu benar-benar berupa sebuah
“pemberontakan” sebagaimana pemberontakan Ranggalawe misalnya. Tetapi
dalam cerita ini, Ma Panji Keta dan Adipati Sadeng dengan mudahnya
diringkus. Kesaktian Gajah Mada sama sekali tak dikeluarkan dalam
sekuel ini.
Ketiga, betapa mudahnya juga Kiai Wirota Wiragati, maling
mumpuni jaman Singasari dan juga sahabat Raden Wijaya, yang semula
membantu mati-matian Ma Panji Keta memberontak terhadap Majapahit
menjadi luruh niatnya oleh bujukan Medang Dangdi dan Kiai Pawagal,
kedua orang sahabatnya itu? Bagaimana mungkin begitu mudahnya ia
dipengaruhi? Saya kira ini juga agak tak wajar, karena lantas terkesan
ceritanya, “Ealah, mek ngono ae.” Ah, ternyata cuman begitu saja.
Namun, ada yang menarik pada sisipan peristiwa Sumpah Amukti Palapa
Gajah Mada itu. Sebagaimana pernah disampaikan penulis pada saat
Bookfair akhir tahun 2006 lalu di Senayan Jakarta, pada cerita itu
disisipkan tafsiran penulis terhadap “hamukti palapa” sebagai sumpah
untuk tidak beristirahat hingga tercapainya cita-cita Gajah Mada.
“Palapa” diartikan sebagai “lara lapa” (jawa), yakni berani menderita
untuk mencapai sebuah cita-cita mempersatukan nusantara. Jadi, hamukti
palapa bukan berpuasa untuk makan buah palapa (kelapa) sebagaimana kita
dengar selama ini. Bagi saya, tafsiran ini sungguh menarik dan patut
diperhitungkan.
Lebih dari itu, apresiasi yang dalam dan juga dua jempol patut
disampaikan kepada penulisnya yang telah dengan piawai meramu isu-isu
tersebut di atas menjadi sebuah cerita yang mengasyikkan ini. Rasanya
tak sabar untuk segera membaca sekuel keempat Gajah Mada terkait dengan
Perang Bubat yang melegenda sekaligus kontroversial itu!
Sumber: Gajah Mada #3: Hamukti Palapa



 04.30
04.30
 iroel
iroel

 Posted in:
Posted in: 










0 komentar:
Posting Komentar